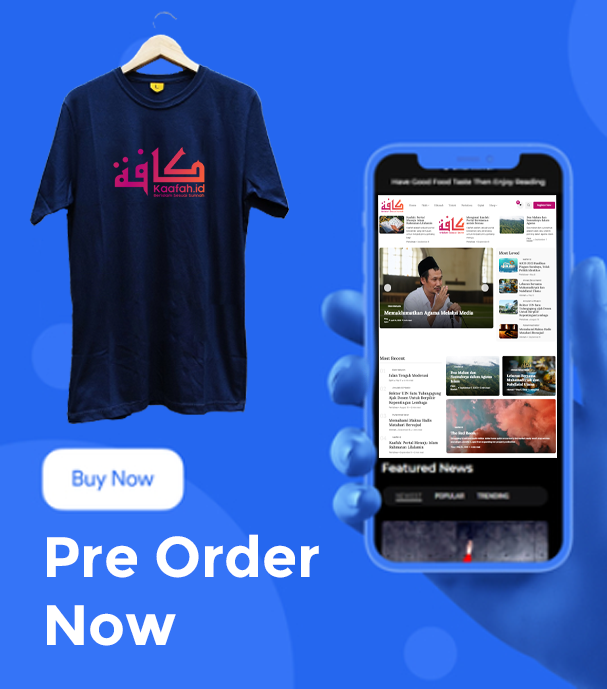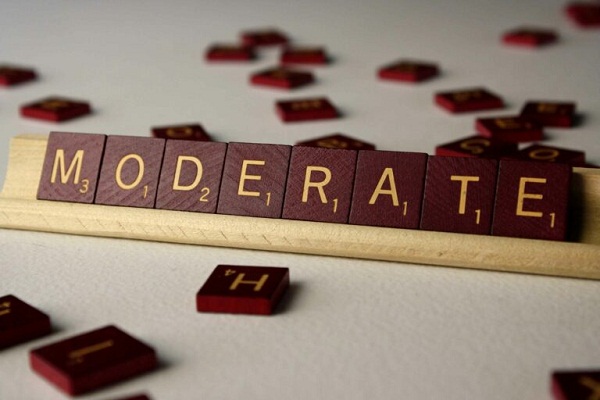“Agama tak butuh suara yang meninggi, melainkan hati yang merendah untuk menginspirasi. Sejarah membuktikan bahwa satu teladan mampu menundukkan lebih banyak hati daripada seribu ancaman”
–Lailatuzz Zuhriyah–
Saya menulis artikel ini sebagai bahan refleksi terkait dengan beberapa kasus kekerasan atas nama agama yang marak terjadi lagi di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Seperti kasus intoleransi yang terjadi di Samarinda, Padang, dan Sukabumi dalam rentang Mei-Juni 2025 ini.
“Tidak ada paksaan dalam agama” (Q.S. Al-Baqarah: 256) merupakan sebuah deklarasi kebebasan hati nurani yang sangat maju untuk konteks abad ke-7 M saat itu. Deklarasi ini sekaligus menjadi sebuah prinsip abadi yang relevan hingga hari ini.
Ayat ini menjadi penuntun moral agar keberagamaan kita tidak berubah menjadi instrumen dominasi. Sebakiknya, sebagai sumber kebaikan bersama, terutama bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat yang majemuk.
Sebuah kalimat sederhana—“Jangan memaksa, jadilah menginspirasi”—ini tetiba terlintas di dalam pikiran saya saat merenungi konflik keagamaan yang terjadi di negeri ini.
Kalimat ini menjadi sebuah seruan yang mencerahkan di tengah lanskap keberagamaan kita yang kadang diwarnai dengan berbagai gesekan.
Kalimat ini juga menyadarkan kepada kita bahwa iman hanya tumbuh di tanah hati yang subur oleh keteladanan. Bukan sebaliknya, di tanah yang dipaksa dengan ancaman atau kekerasan.
Jika menilik kembali dokumen sejarah Islam, dapat kita temukan bahwa dakwah yang bersandar pada pemaksaan, sangat jarang sekali bisa menumbuhkan kesetiaan spiritual yang tulus dari para pengikutnya.
Alih-alih melahirkan pemahaman yang mendalam, sikap tersebut justru akan membangun jarak, memicu resistensi, bahkan akan menciptakan stigma yang negatif terhadap agama.
Di sisi yang lain, ketika dakwah diiringi dengan kesantunan, empati, dan ketinggian akhlak, maka akan dapat menjadi magnet yang memikat hati pengikutnya.
Dalam hal ini, Nabi Muhammad merupakan bukti hidup dalam sejarah, bagaimana teladan personal mampu mengalahkan logika kekerasan. Saat itu, banyak orang yang memeluk Islam bukan karena argumentasi keras atau ancaman, tetapi karena terpikat oleh keluhuran akhlak beliau.
Saat ini, tantangan kita dalam beragama bukan lagi soal memperluas wilayah secara fisik, melainkan bagaimana memperluas pengaruh moral dan spiritual di tengah kompleksitas zaman.
Dalam konteks situasi yang seperti ini, di mana agama sering diseret untuk menjadi bahan bakar konflik, maka pesan “Jangan memaksa, jadilah menginspirasi” akan menjadi kompas etis bagi kita untuk mengarahkan dakwah menuju harmoni sosial.
Sejatinya, dakwah yang menginspirasi tidak hanya sekedar mengajak orang untuk beriman saja, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya, menghargai, serta membangun kerja sama lintas keyakinan di antara mereka.
Agama dalam Cermin Sosiologi
Dalam perspektif sosiologi agama, agama dipandang sebagai sebuah kekuatan yang ambivalen. Di satu sisi agama dapat menjadi “sacred canopy” yang melindungi manusia dari kekosongan makna (Peter L. Berger), tetapi di sisi yang lain, juga dapat berubah menjadi pemicu konflik ketika diiringi dengan fanatisme eksklusif.
Agama sebagai sumber makna, menawarkan orientasi moral dan rasa aman yang eksistensial. Tetapi, ketika agama dikaitkan erat dengan identitas kelompok dan dimobilisasi untuk tujuan politik, maka agama dapat kehilangan sifat universalnya, bahkan berubah menjadi simbol pertarungan kepentingan.
Jika diamati, sebenarnya fenomena wajah ganda agama ini bukan disebabkan oleh ajaran inti yang termaktub di dalam kitab suci. Tetapi karena konstruksi sosial dan politik yang kemudian membentuk cara bagaimana agama ditafsirkan serta didakwahkan kepada khalayak.
Faktor-faktor seperti perebutan kekuasaan, polarisasi identitas, serta kompetisi sumber daya kerap kali memanfaatkan agama sebagai legitimasi.
Implikasinya, pesan moral agama yang seharusnya mengundang kedamaian, justru malah menjadi alat untuk mengukuhkan jarak sosial antara “kami” dan “mereka”.
Dalam bahasa sosiologi, pada akhirnya, yang terjadi bukanlah konflik agama secara murni, melainkan konflik kepentingan yang “dibungkus” dengan narasi-narasi agama.
Dalam konteks Indonesia, kita dapat melihat bagaimana preferensi epistemologi dakwah yang kita lakukan, dapat mempengaruhi citra agama di mata publik.
Pendekatan yang lebih mengedepankan intimidasi maupun ujaran kebencian, akan cenderung memperburuk stereotip negatif tentang agama sebagai sumber intoleransi.
Namun sebaliknya, dakwah yang hadir melalui keteladanan, seperti aksi sosial, gotong royong, atau dialog lintas iman, justru akan memperkuat peran agama sebagai perekat sosial.
Nah, di sinilah pesan “Jangan memaksa, jadilah menginspirasi” menemukan relevansinya, yakni agama akan selalu lebih menarik tatkala dihidupkan melalui keteladanan, bukan paksaan.
Agama dalam Cermin Filsafat Islam
Filsafat Islam berupaya menempatkan akhlak sebagai inti dari peradaban. Filsuf Muslim Al-Farabi, dalam Al-Madinah al-Fadilah (Negara Utama), menegaskan bahwa masyarakat ideal adalah yang dibangun oleh para pemimpin yang memadukan antara kebijaksanaan (hikmah) dengan keluhuran moral.
Kekuasaan, dalam hal ini termasuk otoritas keagamaan, akan kehilangan legitimasi jika dipraktikkan tanpa akhlak yang luhur. Dengan perspektif ini, dakwah yang memaksa bertentangan dengan prinsip madinah fadilah, karena dakwah yang demikian akan meniadakan kebebasan berpikir dan memilih. Padahal kebebasan berpikir dan memilih adalah dua hal yang menjadi syarat bagi tumbuhnya keimanan yang sejati.
Selain itu, Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-nya menegaskan bahwa kekuatan politik atau militer mungkin akan dapat menaklukkan wilayah. Tetapi belum tentu akan dapat menaklukkan hati.
Ibnu Khaldun membedakan antara kekuasaan yang berbasis paksaan dengan kekuasaan yang lahir dari asabiyyah yang positif, yakni ikatan sosial yang dibangun atas rasa percaya dan kebersamaan.
Dalam konteks dakwah, asabiyyah yang positif ini terbangun ketika umat merasakan bahwa ajakan agama dapat memberikan kemaslahatan, bukan hanya sekedar memaksakan doktrin saja.
Menghadirkan Harmoni Sosial
Indonesia sebagai negara yang plural, merupakan ladang yang subur bagi dakwah yang menginspirasi. Di tengah keragaman budaya, etnis, dan agama, pendekatan ini memposisikan akhlak di garis yang paling depan.
Dakwah yang menginspirasi justru memandang perbedaan sebagai peluang untuk dapat saling belajar, bukan malah sebaliknya, yakni memandang perbedaan sebagai sebuah ancaman dan harus diseragamkan.
Nilai-nilai universal dalam dakwah yang menginspirasi, seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pesan agama dengan realitas sosial.
Oleh karena itu, kekuatan dakwah sejatinya tidak diukur dari seberapa banyak orang yang “menang” dalam debat, melainkan dari seberapa banyak hati yang tersentuh untuk berbuat kebaikan.
Living Islam di Indonesia
Konsep living Islam dapat menjadi salah satu solusi di tengah intoleransi yang marak terjadi. Living Islam menggambarkan bagaimana ajaran Islam tidak hanya berhenti pada tataran teks dan teori saja, tetapi hidup dalam praktik sehari-hari umatnya.
Praktik living Islam di Indonesia nampak dalam berbagai ekspresi budaya yang ramah dan inklusif dari masyarakatnya.
Contohnya seperti gotong royong dalam membangun rumah ibadah, tradisi tahlilan dan yasinan yang mempererat tali silaturahmi, sedekah bersama yang melibatkan warga lintas agama, hingga keramahan sederhana yang kerap kali kita jumpai, seperti senyum tetangga atau sapaan hangat di pasar.
Semua bentuk kegiatan ini dapat menjadi bentuk dakwah yang tidak memerlukan slogan besar, namun dapat terasa langsung manfaatnya di tengah masyarakat kita.
Kekuatan dari living Islam terletak pada kemampuannya dalam mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, sehingga ajaran agama menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat, bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar.
Dalam konteks ini, upaya untuk membumikan dan mempraktikkan konsep living Islam dapat menjadi benteng kultural terhadap radikalisme. Hal ini karena living Islam mengakar pada nilai kebersamaan, penghargaan terhadap perbedaan, serta solidaritas sosial.
Ketika bentuk-bentuk praksis living Islam ini terus dipelihara, maka dakwah akan hadir dalam wajah yang menginspirasi dan menyatukan, bukan malah memecah-belah.
Maka, di sinilah pesan “Jangan memaksa, jadilah menginspirasi” akan dapat menemukan wujudnya secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia.
Saat ini, mungkin kita sudah kenyang dengan berbagai retorika dan perdebatan yang panjang perihal perbedaan.
Oleh sebab itu, yang dibutuhkan saat ini adalah figur dan komunitas yang mampu menjadi teladan yang nyata, yang mampu menunjukkan bahwa agama dapat mewujudkan perdamaian, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan rasa saling percaya.
Kalimat seruan “Jangan memaksa, jadilah menginspirasi” merupakan panggilan moral untuk setiap dai, pendidik, tokoh agama, maupun semua umat beragama.
Karena pada akhirnya, dakwah yang tulus dengan dibalut oleh akhlak yang mulia, dan dihidupkan dalam perilaku sehari-hari ini lah yang akan dapat mengetuk hati lebih kuat, ketimbang seribu kata yang diucapkan dengan nada yang memaksa.
Penulis:
Lailatuzz Zuhriyah (Kepala Pusat Penelitian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Sekretaris Forum Kapuslit PTKIN)