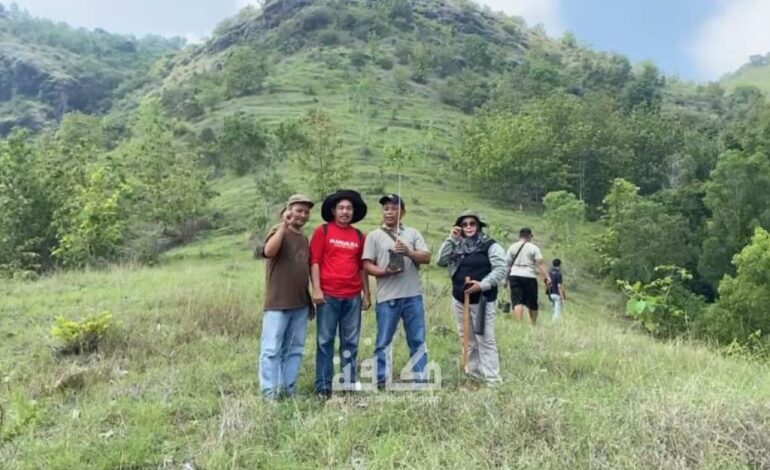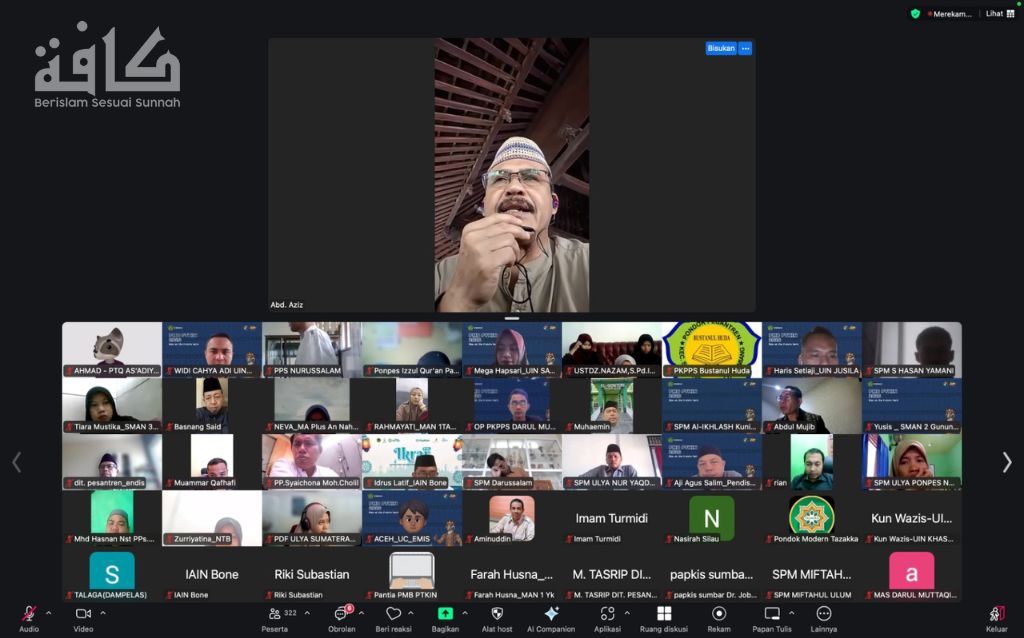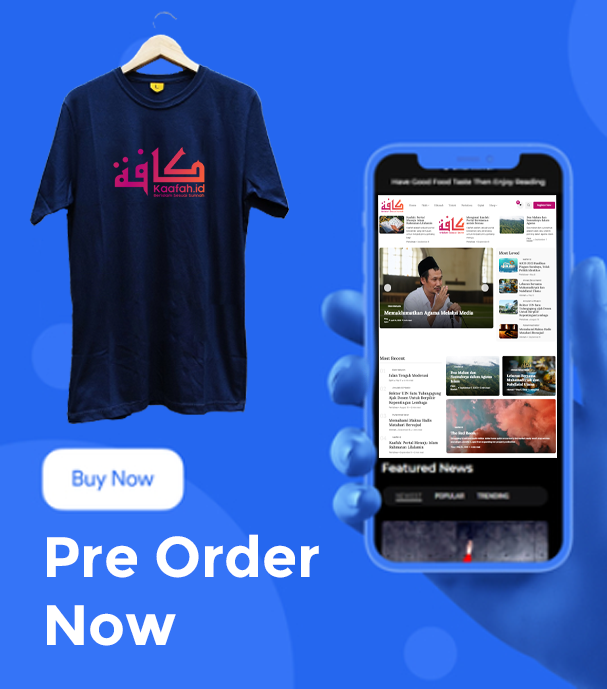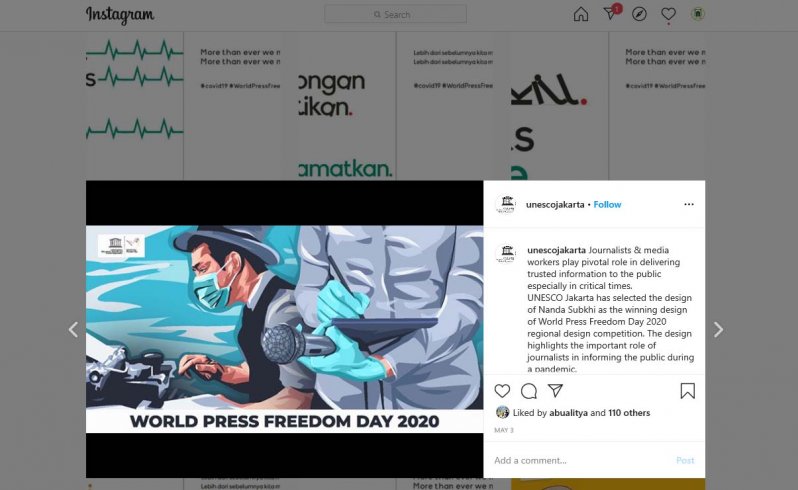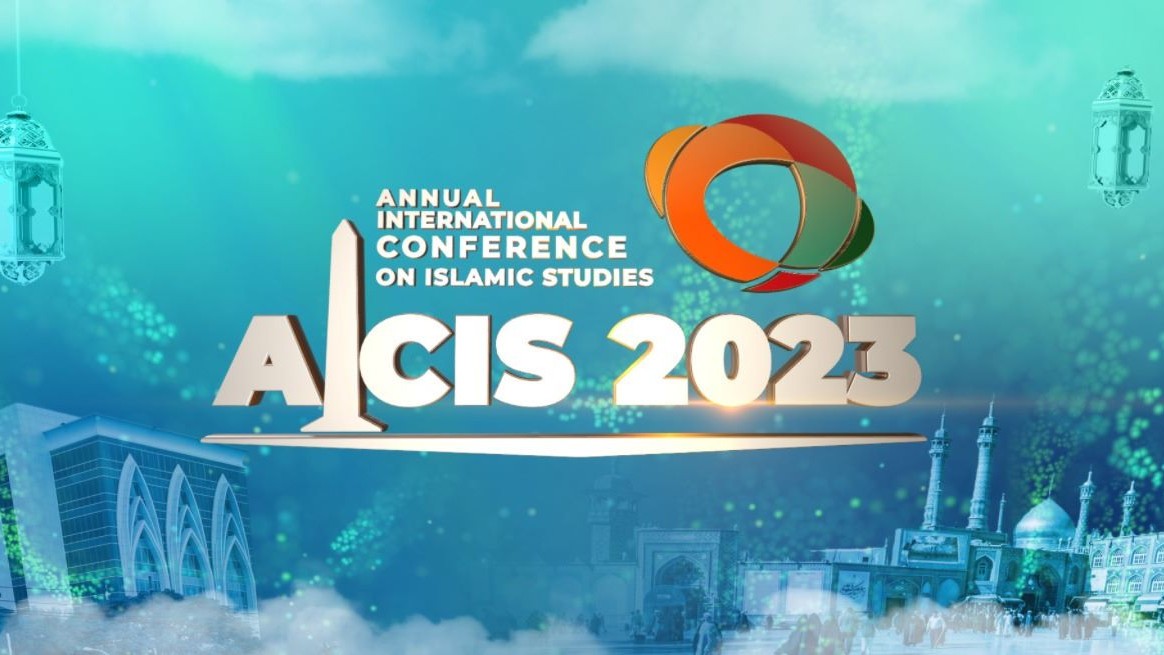Perbincangan tentang feminisme, khususnya di Indonesia, seringkali dibayangi oleh prasangka dan salah paham yang kental. Banyak yang menganggapnya sebagai ide ‘Barat’ yang asing, bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran atau bahkan ajaran agama, terutama Islam, yang menjadi identitas mayoritas bangsa. Namun, di tengah hiruk-pikuk dan ketegangan wacana ini, muncul sebuah narasi yang menawarkan jalan tengah yang harmonis dan transformatif: Feminisme Islam. Gerakan pemikiran ini kini semakin menemukan ruangnya di kelas-kelas perkuliahan dan diskusi ilmiah, mengubah cara pandang terhadap relasi laki-laki dan perempuan, dari yang semula dianggap sebagai dua kubu yang saling berlawanan atau bersaing, menjadi mitra sejajar dalam bingkai keadilan dan spiritualitas.
Feminisme Islam muncul sebagai jawaban terhadap ketidakadilan gender yang berkembang dalam praktik keagamaan dan sosial di masyarakat Muslim. Gerakan ini berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis secara hermeneutik kontekstual, dengan menempatkan keadilan dan egalitarianisme sebagai prinsip utama.
Fakta nyata baru-baru ini adalah munculnya berbagai inisiatif pendidikan dan kebijakan yang memperjuangkan hak perempuan dalam dunia pendidikan Islam. Sebagai contoh, di Indonesia, Pembangunan Pesantren perempuan modern di beberapa daerah, seperti pesantren berbasis gender di Jakarta dan Surabaya, menandai sebuah langkah penting dalam rekonstruksi pemikiran tentang peran perempuan dalam Islam. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Madrasah (PPPM) secara aktif memuat kurikulum yang mempromosikan kesetaraan gender dan mempromosikan tafsir al-Qur’an yang mendukung keadilan gender.
Di kelas-kelas, khususnya pada program studi keagamaan atau humaniora, diskusi tentang Feminisme Islam membawa angin segar dan perspektif yang lebih inklusif. Mahasiswa diajak untuk tidak lagi melihat gender—atau perjuangan kesetaraan—sebagai ‘lawan’ yang harus dikalahkan atau dihindari, tetapi sebagai ‘teman diskusi’ yang harus dipahami secara mendalam dan diajak bekerja sama. Konsepnya sederhana namun mendalam: laki-laki dan perempuan diciptakan setara sebagai hamba Allah (‘abd) dan sebagai wakil-Nya di bumi (khalifah fil ardh), dengan tanggung jawab moral, spiritual, dan kemanusiaan yang sama. Perbedaan yang ada hanyalah pada fungsi biologis dan sosial tertentu yang bersifat fungsional, bukan pada derajat kemanusiaan, kecerdasan, atau spiritualitas.
Inti dari Feminisme Islam yang dibahas di kelas adalah kegiatan reinterpretasi atau penafsiran ulang (hermeneutika) terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini secara tradisional dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Mereka menggunakan pendekatan yang kritis, historis, dan kontekstual. Contoh yang paling sering dibahas dan dikritisi adalah mengenai ayat-ayat yang kerap dijadikan dasar pembenaran bahwa laki-laki adalah pemimpin mutlak bagi perempuan (seperti penafsiran kaku atas Q.S. An-Nisa’ ayat 34), atau hadis-hadis yang seolah-olah merendahkan akal, kesaksian, atau kemampuan kepemimpinan perempuan. Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud dengan metode tafsir holistiknya, Fatima Mernissi dengan kritiknya terhadap penafsiran hadis misoginis, hingga para cendekiawan Muslim progresif di Indonesia seperti Musdah Mulia dan KH Husein Muhammad (dengan konsep Mubadalah atau resiprokal), menyajikan cara pandang baru yang ramah gender.
Dalam konteks pendidikan, Feminisme Islam sangat menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi perempuan dan laki-laki. Penekanan ini penting, sebab di banyak daerah, pandangan tradisional yang bias gender masih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dengan dalih bahwa perempuan pada akhirnya hanya akan mengurus rumah tangga. Feminisme Islam menantang argumen tersebut dengan basis ajaran agama. Perempuan yang berpendidikan adalah pilar utama masyarakat yang kuat. Mereka adalah pendidik pertama bagi generasi berikutnya dan memiliki hak serta kewajiban untuk berkontribusi secara penuh di ranah publik—baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun keagamaan. Fatima Mernissi, misalnya, secara konsisten menyuarakan bahwa pendidikan adalah jalan keluar bagi perempuan dari belenggu patriarki.
Kesenjangan gender sering masih terjadi dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial. Berita terkini menunjukkan adanya upaya dari berbagai komunitas dan aktivis perempuan Muslim untuk menuntut perubahan kebijakan pendidikan yang patriarkal, serta mendorong interpretasi agama yang lebih adil dan mengedepankan hak asasi perempuan.
Misalnya, keberhasilan tokoh perempuan seperti Amina Wadud, seorang akademisi dan aktivis feminis Islam internasional—yang berhasil memimpin salat jemaah pria dan wanita di beberapa negara, termasuk di luar negara-negara mayoritas Muslim, menjadi simbol kebangkitan tafsir baru yang merespons kebutuhan keadilan gender dalam konteks modern.
Meski demikian, proses rekonstruksi ini tidaklah mulus. Banyak kelompok konservatif dan tradisional yang menentang interpretasi reformis ini. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran asli dan bisa melemahkan kedudukan otoritas agama.
Namun, dinamika ini membuka peluang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana pendidikan Islam dapat memperlihatkan keadilan gender tanpa mengorbankan esensi ajaran agama. Penguatan komunitas dan lembaga edukatif yang mendukung feminisme Islami menjadi kunci utama dalam mempercepat perubahan paradigma ini.
Epistemologi integrasi dalam pendidikan Islam berangkat dari filsafat keilmuan yang menegaskan pentingnya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern secara harmonis. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran tokoh seperti Hassan Hanafi dan Amin Abdullah yang menolak dikotomi ilmu, dan berusaha membangun sebuah kerangka epistemologi yang saling menyokong dan berinteraksi.
Berita terbaru menyoroti munculnya pusat studi dan kurikulum yang mengadopsi pendekatan ini di universitas Islam seperti UIN Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga. Mereka mengembangkan kurikulum yang menggabungkan ilmu tafsir, hadis, filsafat, sains, dan teknologi dalam satu kerangka komprehensif.
Implementasi epistemologi ini tercermin pada munculnya program studi baru yang mengintegrasikan teknologi digital dan ilmu sosial humaniora dengan studi Islam. Di kampus-kampus tersebut, mahasiswa dan dosen didorong untuk melakukan penelitian lintas disiplin, seperti mengkaji dampak teknologi dalam tafsir Qur’an digital, atau studi tentang penggunaan AI dalam pendidikan keislaman.
Berita nyata menunjukkan, misalnya, peluncuran platform digital yang memuat tafsir Qur’an berbasis AI dan big data. Ini memperlihatkan paradigma inovatif pendidikan Islam yang tidak sekadar bersifat tekstual, tetapi juga interaktif dan berbasis data.
Meskipun demikian, tantangan besar dalam menerapkan epistemologi integrasi ini adalah resistensi dari kalangan konservatif dan kekhawatiran terhadap hilangnya identitas keislaman yang otentik. Selain itu, aspek kurikulum harus mampu menyeimbangkan antara keilmuan ilmiah dan nilai-nilai spiritual serta moral.
Dalam konteks ini, penerapan epistemologi integrasi menjadi penting, karena dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antara tradisi dan inovasi, serta menjaga kesinambungan keilmuan Islam secara dinamis dan adaptif.
Editor: Ahmad Misbakhul Amin